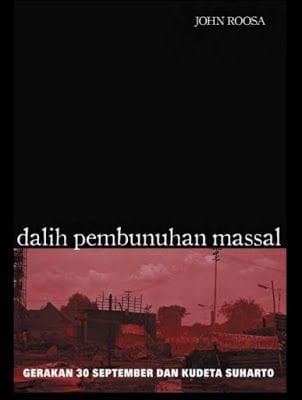Judul Buku : Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia (dari tahun 1905-1926)
Penulis : Dipa Nusantara Aidit
Penerbit: Jajasan Pembaruan
Isi : Vol 1, 64 halaman
Cetakan : Satu, Djakarta 1952
Di bawah bayang-bayang omnibus law, buruh hari ini berdiri di posisi apa: subjek yang menentukan arah kesejahteraan atau sekadar bayangan yang digeser demi kelancaran arus investasi? Pertanyaan itu bergaung sejak kalimat pertama ketika membaca Sejarah Gerakan Buruh Indonesia karya D.N. Aidit, seolah buku ini menolak tetap menjadi arsip sunyi. Aidit menulis dari masa ketika penindasan masih berbicara dengan cambuk dan laras senapan; kita membacanya di masa ketika penindasan berbicara dengan pasal, grafik, dan jargon efisiensi. Tetapi logikanya sama: kerja diperas, suara dibungkam, dan buruh diminta percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh tangan-tangan yang tak pernah berkeringat. Resensi ini berangkat dari kegelisahan itu—bahwa omnibus law bukan sekadar hukum, melainkan kabut yang menutupi siapa yang bekerja, siapa yang berkuasa, dan siapa yang terus-menerus diminta bersabar. Membaca Aidit hari ini terasa seperti membuka cermin retak. Wajah yang kita lihat mungkin berbeda zaman, tetapi luka strukturalnya masih basah dan belum sempat mengering.
Buku Aidit berseberangan dengan omnibus law bukan pertama-tama karena perbedaan ideologi yang kasat mata, melainkan karena cara memandang manusia yang bekerja. Saat membaca Aidit, saya merasakan satu penegasan yang nyaris kasar: buruh adalah pusat dari seluruh bangunan sosial, bukan roda cadangan yang bisa diganti demi efisiensi. Omnibus law, sebaliknya, membuat saya merasa buruh diperlakukan seperti variabel teknis—angka yang boleh ditekan, dilenturkan, atau dipangkas selama grafik investasi tetap tampak sehat. Di titik ini, pertentangannya bukan sekadar politis, tetapi etis. Aidit menulis seolah kesejahteraan hanya mungkin jika buruh berdaulat atas kerjanya, omnibus law berbicara seolah kesejahteraan akan “menetes” dengan sendirinya jika buruh mau menyesuaikan diri.
Secara personal, benturan itu terasa ketika Aidit berkali-kali menegaskan bahwa hukum selalu lahir dari pertarungan kekuasaan. Ia tidak percaya pada hukum yang netral, apalagi hukum yang mengaku teknokratis. Membaca omnibus law dengan kacamata Aidit membuat saya sulit menerima narasi bahwa pelemahan perlindungan buruh adalah harga rasional demi pertumbuhan. Aidit justru mengajarkan kecurigaan: siapa yang diuntungkan ketika kerja dibuat fleksibel, ketika jaminan dipereteli, atau ketika risiko dialihkan ke pundak pekerja? Jawabannya terlalu sering bukan buruh. Karena itu buku ini terasa berseberangan secara naluriah—ia menolak bahasa manis yang menyamarkan pemindahan beban dari negara dan modal ke tubuh buruh.
Yang paling membuat jarak itu terasa tajam adalah soal posisi buruh dalam menentukan masa depan. Aidit menulis dengan keyakinan bahwa buruh harus menjadi subjek politik dan ikut menentukan arah kesejahteraan kolektif, meski harus berhadapan dengan negara. Omnibus law justru memindahkan buruh ke pinggir meja perundingan, menjadikannya objek yang diatur demi stabilitas dan kepercayaan pasar. Membaca keduanya bersamaan membuat saya sadar: buku Aidit dan omnibus law berbicara tentang “kesejahteraan” dengan kamus yang sama sekali berbeda. Yang satu melihat kesejahteraan sebagai hasil perebutan kuasa, sementara yang lain menjualnya sebagai janji administrasi. Di sanalah pertentangannya menjadi tak terjembatani—dan bagi saya, tak mungkin dibaca tanpa memilih posisi.
Menarik diskusi buku Aidit ke pembahasan omnibus law bukanlah upaya memaksakan masa lalu ke masa kini, melainkan cara jujur untuk menguji apakah sejarah benar-benar bergerak, atau hanya berganti kostum. Bagi saya, buku Sejarah Gerakan Buruh Indonesia akan kehilangan daya gigitnya jika diperlakukan sebagai bacaan arsip—dikagumi ketajamannya, lalu disimpan kembali di rak. Aidit menulis sejarah bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipakai membaca relasi kuasa yang sedang bekerja. Omnibus law adalah medan aktual tempat tesis-tesis itu diuji secara telanjang.
Diskusi ini perlu ditarik ke omnibus law karena di sanalah pertanyaan inti Aidit menemukan konteks barunya: siapa yang menentukan arah kesejahteraan kolektif? Aidit menjawabnya dengan terang—buruh, jika dan hanya jika mereka hadir sebagai subjek politik. Omnibus law justru bergerak ke arah sebaliknya, memindahkan pusat keputusan ke negara dan modal dengan dalih efisiensi. Tanpa menarik garis ini, buku Aidit berisiko dibaca sebagai sejarah heroik yang selesai, bukan sebagai peringatan tentang pola kekuasaan yang berulang.
Secara personal, mengaitkan keduanya adalah cara untuk menolak ilusi bahwa hukum hari ini lebih netral atau lebih rasional daripada hukum kolonial yang dikritik Aidit. Bahasa omnibus law memang lebih halus, prosedurnya lebih modern, tetapi logika dasarnya terasa serupa: kerja harus lentur, buruh harus adaptif, dan ketimpangan dianggap konsekuensi yang bisa dikelola. Aidit mengajarkan saya untuk tidak terpukau oleh bahasa kebijakan, melainkan bertanya siapa yang menanggung risiko dan siapa yang menikmati hasilnya. Pertanyaan itu menemukan relevansinya justru ketika dibenturkan dengan omnibus law.
Lebih jauh, menarik diskusi ini ke omnibus law adalah reposisi etis. Ia memaksa pembaca—termasuk saya, untuk berhenti bersikap aman. Membaca Aidit tanpa mengaitkannya dengan kebijakan ketenagakerjaan hari ini berarti membiarkan ketajamannya tumpul oleh jarak waktu. Dengan menariknya ke omnibus law, buku ini kembali menjadi apa yang ia niatkan sejak awal: alat untuk berpihak, untuk curiga, dan untuk menolak anggapan bahwa kesejahteraan buruh bisa dititipkan sepenuhnya pada hukum yang tidak mereka kuasai.
Di titik itu, diskusi ini bukan soal menyamakan dua zaman, melainkan menyambungkan luka struktural yang belum sembuh. Aidit memberi bahasa untuk membaca luka itu, omnibus law menunjukkan bahwa luka tersebut masih terbuka. Tanpa jembatan itu, kita hanya membaca sejarah. Dengan jembatan itu, kita sedang membaca diri kita sendiri di dalam sejarah yang belum selesai.
Buku Sejarah Gerakan Buruh Indonesia (1952) karya D.N. Aidit lahir dari satu keyakinan radikal: buruh bukan sekadar korban sejarah, melainkan subjek politik yang secara sadar membentuk arah zaman. Dibaca hari ini—di bawah bayang-bayang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, buku ini terasa seperti arsip yang tiba-tiba hidup kembali, bukan karena nostalgianya, melainkan karena relevansinya yang menyengat. Aidit menulis dari era ketika buruh berhadapan langsung dengan kolonialisme dan kapital asing, kemudian kita membacanya di era ketika buruh berhadapan dengan negara sendiri yang bertindak sebagai manajer investasi.
Secara metodologis, Aidit menyusun sejarah buruh sebagai sejarah perjuangan kelas yang terorganisir, bukan deretan peristiwa industrial semata. Serikat buruh, mogok kerja, dan organisasi massa ditempatkan sebagai infrastruktur politik, bukan pelengkap pembangunan. Dalam kerangka ini, hukum ketenagakerjaan tidak pernah netral, ia selalu mencerminkan relasi kuasa yang dominan. Di titik inilah jembatan lintas era bisa dibangun. Jika pada awal abad ke-20 hukum kolonial berfungsi menertibkan tenaga kerja demi akumulasi kapital imperial, maka omnibus law bekerja dengan logika serupa, menyederhanakan perlindungan buruh demi “iklim investasi.” Bahasa berubah, tetapi orientasi kekuasaan tetap.
Aidit berangkat dari tesis bahwa kekuatan buruh terletak pada kolektivitas dan kesadaran politik, bukan pada kemurahan regulasi. Sejarah mogok dan perlawanan yang ia paparkan menunjukkan satu pola: setiap kemajuan buruh lahir dari konflik terbuka dengan negara dan modal, bukan dari konsensus teknokratis. Di bawah omnibus law, pola itu berulang dalam bentuk baru. Fleksibilisasi kerja, perluasan outsourcing, dan pelemahan pesangon bukanlah anomali kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari model pembangunan yang memposisikan buruh sebagai variabel biaya. Aidit membantu kita melihat bahwa yang berubah bukan substansinya, melainkan mekanisme legitimasi: dulu kekerasan kolonial, kini narasi efisiensi dan daya saing.
Pada bab awal, Aidit meletakkan fondasi konseptual, di mana buruh diposisikan sebagai subjek sejarah yang lahir dari relasi produksi kolonial. Kekuatan bab ini terletak pada keberaniannya membongkar mitos “netralitas” kolonialisme ekonomi. Kapitalisme kolonial digambarkan bukan sebagai mesin modernisasi, melainkan sistem eksploitasi terorganisir yang membutuhkan tenaga kerja murah dan patuh. Secara kritis, bab ini sangat efektif sebagai pembuka karena langsung menetapkan kerangka konflik kelas. Namun, di sisi lain, Aidit cenderung menyederhanakan diferensiasi buruh (perkebunan, pelabuhan, kerajinan, urban informal) menjadi satu blok homogen. Kelemahan ini terasa ketika kita membandingkannya dengan kompleksitas struktur kerja hari ini.
Memasuki bab tentang lahirnya organisasi buruh dan serikat awal, Aidit menunjukkan keunggulan historisnya. Ia menulis dengan detail mengenai embrio kesadaran kolektif buruh, hubungan mereka dengan organisasi politik, dan bagaimana mogok kerja menjadi bahasa politik pertama kelas pekerja. Bab ini tajam karena menolak pandangan evolusioner-liberal yang melihat serikat sebagai produk “kemajuan alami.” Bagi Aidit, serikat lahir dari konflik, bukan konsensus. Kritik yang patut diajukan: Aidit terlalu cepat mengafirmasi garis politik tertentu sebagai “representasi objektif buruh,” sehingga dinamika internal—perpecahan strategi, kepentingan lokal, atau pragmatisme buruh sendiri kurang mendapat ruang reflektif.
Pada bab yang membahas periode represi kolonial dan kriminalisasi gerakan buruh, analisis Aidit mencapai intensitas politiknya. Negara kolonial tampil sebagai aparatus koersif yang secara sistematis menggunakan hukum, polisi, dan militer untuk mematahkan organisasi buruh. Di sini, Aidit berhasil menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan sejak awal adalah instrumen kekuasaan, bukan pelindung netral. Bab ini sangat relevan lintas zaman, pembaca hari ini dengan mudah menemukan paralelnya dalam pasal-pasal omnibus law yang “legal” namun melemahkan posisi tawar buruh. Kelemahannya terletak pada minimnya refleksi atas strategi alternatif selain konfrontasi terbuka, seolah sejarah hanya bergerak melalui eskalasi konflik frontal.
Berlanjut ke bab tentang peran politik kiri dan keterkaitan buruh dengan perjuangan nasional, Aidit tampil paling ideologis. Ia secara eksplisit menautkan gerakan buruh dengan agenda anti-imperialisme dan revolusi nasional. Secara analitis, bab ini kuat karena menegaskan bahwa kemerdekaan politik tanpa emansipasi buruh adalah kemerdekaan semu. Namun secara kritis, di sinilah buku ini paling problematik. Aidit cenderung menutup ruang bagi pembacaan non-revolusioner atau strategi gradual, seakan-akan semua jalur di luar politik kelas radikal adalah bentuk pengkhianatan. Untuk pembaca lintas generasi, bab ini perlu dibaca dengan jarak kritis, bukan penelanan ideologis.
Pada bab-bab akhir, ketika Aidit menarik garis besar pelajaran sejarah dan proyeksi masa depan gerakan buruh, buku ini berubah dari historiografi menjadi manifesto. Aidit menegaskan bahwa tanpa organisasi kuat dan kesadaran kelas, buruh akan selalu menjadi objek kebijakan, bukan pembentuknya. Kekuatan bagian ini adalah konsistensinya: sejarah tidak dibiarkan netral, tetapi dipaksa berbicara secara politis. Kelemahannya, sekali lagi, adalah asumsi tentang linearitas sejarah—seolah arah perjuangan buruh sudah jelas dan tinggal dijalankan.
Marginalia
Refleksi Aidit tentang buruh sebagai subjek politik tidak berhenti pada pengakuan normatif bahwa buruh “penting” atau “harus dilindungi”. Ia melangkah jauh lebih radikal: buruh, bagi Aidit, adalah wadah historis tempat arah kesejahteraan kolektif diputuskan atau digagalkan. Sejauh itulah posisinya—dan di situlah sekaligus kekuatan serta batas pemikirannya.
Aidit melihat buruh bukan sebagai kelompok kepentingan sektoral, melainkan sebagai kelas sosial yang secara struktural berada di jantung produksi. Karena buruhlah yang menggerakkan ekonomi, maka secara logis merekalah yang paling berhak menentukan bagaimana surplus didistribusikan dan untuk siapa pembangunan dijalankan. Dalam kerangka ini, kesejahteraan kolektif bukan hasil kemurahan negara, melainkan konsekuensi dari pergeseran relasi kuasa. Negara, hukum, dan kebijakan hanya akan berubah jika buruh hadir sebagai kekuatan politik yang terorganisir, sadar, dan siap berkonflik.
Refleksi ini mencapai titik paling tajam ketika Aidit menolak memisahkan perjuangan ekonomi dari perjuangan politik. Upah, jam kerja, dan kondisi kerja tidak pernah ia anggap sebagai persoalan teknis. Semuanya adalah ekspresi dari siapa yang berkuasa. Karena itu, serikat buruh baginya bukan sekadar alat negosiasi, melainkan infrastruktur politik kelas pekerja. Tanpa itu, kesejahteraan kolektif akan selalu bersifat rapuh—mudah ditarik kembali ketika rezim berganti atau krisis datang. Di sini Aidit sangat konsisten, buruh yang tidak berpolitik akan selalu dipolitisasi oleh kepentingan lain.
Namun refleksi Aidit juga memiliki batas yang jelas. Ia cenderung memandang buruh sebagai subjek yang secara potensial homogen dan progresif, seakan kesadaran politik adalah sesuatu yang niscaya jika kondisi objektif terpenuhi. Dalam praktiknya, sejarah—termasuk sejarah setelah Aidit menunjukkan bahwa buruh bisa terfragmentasi, pragmatis, bahkan terseret dalam agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan kolektifnya sendiri. Di titik ini, Aidit lebih normatif daripada reflektif: ia menulis tentang buruh sebagaimana seharusnya, bukan selalu sebagaimana adanya.
Meski begitu, justru di tengah keterbatasan itulah refleksi Aidit tetap relevan hari ini. Ketika buruh direduksi menjadi angka statistik ketenagakerjaan, ketika kesejahteraan kolektif diserahkan pada mekanisme pasar dan logika investasi, Aidit mengingatkan satu hal mendasar: tanpa subjek politik yang sadar dan terorganisir, kesejahteraan hanyalah janji kebijakan. Omnibus law, fleksibilisasi kerja, dan normalisasi ketimpangan adalah bukti bahwa ketika buruh dikeluarkan dari arena penentuan arah, hasilnya selalu regresif.
Refleksi normatif menjadi celah pemikiran Aidit justru karena ia menulis dari keyakinan politik, bukan dari jarak analitis. Aidit tidak sedang mengamati buruh sebagai fenomena sosial yang ambigu dan sering kontradiktif, ia menuliskannya sebagai subjek historis yang harus ada agar arah sejarah bergerak menuju emansipasi. Di titik ini, normativitas bukan kecelakaan metodologis, melainkan pilihan sadar—dan setiap pilihan sadar selalu membuka celah.
Celah pertama muncul dari asumsi tentang kesadaran yang linear. Aidit berangkat dari premis klasik materialisme historis: kondisi objektif penindasan pada akhirnya akan melahirkan kesadaran subjektif. Buruh yang dieksploitasi, dalam pandangan ini, akan terdorong untuk berorganisasi dan berpolitik. Masalahnya, sejarah—bahkan pada masa Aidit sendiri—menunjukkan bahwa penderitaan tidak otomatis menghasilkan kesadaran politik. Ia justru sering melahirkan kepatuhan, ketakutan, atau adaptasi pragmatis. Di sinilah refleksi normatif Aidit menjadi rapuh: ia menggambarkan buruh sebagaimana harus bereaksi, bukan sebagaimana mereka sering benar-benar bereaksi.
Celah kedua terletak pada homogenisasi subjek buruh. Demi koherensi politik, Aidit menyederhanakan keragaman pengalaman buruh lintas sektor, etnis, wilayah, dan tingkat keterampilan ke dalam satu identitas kelas yang relatif utuh. Ini efektif sebagai seruan mobilisasi, tetapi lemah sebagai analisis sosial jangka panjang. Ketika buruh tidak bertindak serempak atau bahkan berseberangan kepentingan, kerangka Aidit kesulitan menjelaskan kegagalan itu tanpa jatuh pada tudingan “kesadaran palsu” atau pengkhianatan.
Celah ketiga adalah optimisme politis terhadap organisasi. Aidit menempatkan serikat dan partai sebagai kendaraan rasional yang secara inheren mengartikulasikan kepentingan buruh. Padahal, organisasi juga bisa birokratis, elitis, bahkan terpisah dari basisnya sendiri. Karena refleksi Aidit bersifat normatif, ia lebih sering mengasumsikan organisasi sebagai solusi ketimbang memeriksanya sebagai masalah yang mungkin muncul dari dinamika kekuasaan internal.
Lebih dalam lagi, normativitas Aidit berakar pada horizon sejarah yang teleologis—keyakinan bahwa sejarah bergerak menuju arah tertentu yang lebih adil. Keyakinan ini memberi energi politik, tetapi mengurangi sensitivitas terhadap kemungkinan stagnasi, regresi, atau mutasi bentuk penindasan. Ketika kesejahteraan kolektif gagal terwujud, kerangka ini cenderung mencari penyebab di luar struktur teorinya, bukan pada keterbatasan teori itu sendiri.
Normativitasnya memperlihatkan ketegangan abadi antara teori sebagai alat analisis dan teori sebagai senjata politik. Aidit memilih yang kedua dan konsekuensinya adalah penyederhanaan. Bagi pembaca hari ini, tugasnya bukan menertawakan celah itu, melainkan memanfaatkannya: membaca Aidit sebagai peta aspirasi, sambil menyadari bahwa medan sosial selalu lebih berliku daripada peta mana pun.
Dengan kata lain, refleksi normatif Aidit bocor karena ia terlalu yakin pada arah, terlalu percaya pada subjek, dan terlalu berharap pada organisasi. Tetapi justru dari kebocoran itulah kita bisa melihat batas antara keinginan sejarah dan kenyataan sosial—batas yang masih relevan untuk diperdebatkan sampai sekarang.
Kritik saya pada Aidit justru berangkat dari kekuatan utamanya: normativitas yang terlalu percaya diri. Ia menulis buruh bukan sebagaimana mereka hidup, ragu, dan sering kali terpaksa berkompromi, melainkan sebagaimana mereka harus menjadi agar sejarah bergerak ke arah yang ia yakini. Di titik ini, Aidit menekan realitas agar patuh pada visi. Buruh diasumsikan akan sadar ketika dieksploitasi, akan bersatu ketika ditindas, dan akan memilih politik kelas ketika diberi pilihan—padahal pengalaman sosial menunjukkan sebaliknya lebih sering terjadi. Normativitas ini memberi nyala, tetapi juga menutup mata pada fakta bahwa penindasan kerap melahirkan kelelahan, ketakutan, bahkan keinginan untuk sekadar selamat, bukan kesadaran revolusioner.
Yang membuat saya merasa tertekan sebagai pembaca adalah cara normativitas Aidit menggeser kegagalan dari teori ke subjek. Ketika buruh tidak bergerak sesuai harapan, problemnya bukan dibaca sebagai keterbatasan kerangka analisis, melainkan sebagai kurangnya kesadaran buruh itu sendiri. Di sini Aidit berhenti mendengarkan realitas dan mulai menghakiminya. Ia terlalu cepat yakin bahwa organisasi selalu mewakili kepentingan buruh, bahwa garis politik tertentu niscaya benar, dan bahwa sejarah berada di pihaknya. Sikap ini tegas, tetapi juga berbahaya, karena ia menyederhanakan manusia yang bekerja menjadi figur ideal yang siap dikorbankan demi visi besar. Kritik ini bukan untuk menyingkirkan Aidit, melainkan untuk menempatkannya secara proporsional: sebagai pemikir yang memberi arah dan keberanian berpihak, tetapi yang normativitasnya perlu terus ditekan balik agar tidak berubah dari visi emansipasi menjadi dogma yang membungkam kenyataan.
Penulis: Muhammad Hermawan Sutanto
Editor: Alfida