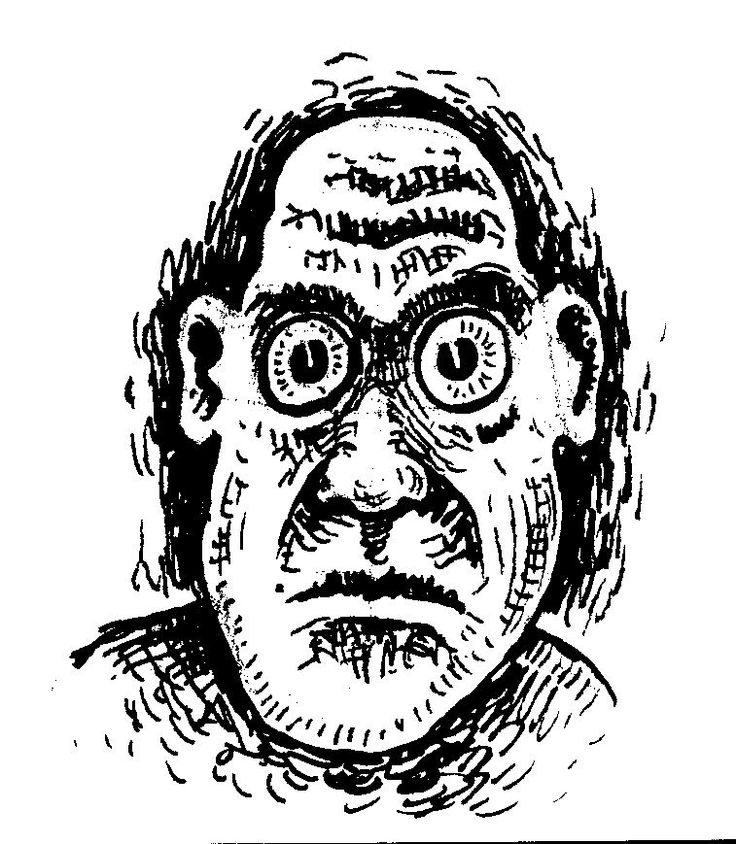
ilustrasi karya uhperry diambil dari pinterest
Tabik, warga Uin Pucangan, PMII Tosuro, dan orang-orang kalahan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Hermawan Sutanto, teman satu angkatan Muhammad Fiam Setyawan. Saya bukan kader PMII, tapi bolehlah saya anggap Fiam adalah sahabat saya, mengingat kami berdua merupakan leting AFI 2020. Fiam sarjana dan saya tidak. Karena sama-sama diasuh oleh “rahim filsafat”, saya merasa punya tanggung jawab moral sebagai sahabat baik Fiam untuk mengurai opini beliau dengan tajuk “Menanggalkan Atribut Biru Kuning” yang santer akan logical fallacies dan misunderstanding. Sebelumnya, karya opini Fiam dimaksudkan untuk klarifikasi atau mendiskreditkan opini yang berjudul “Kampus Pergerakan Indonesia” karya Hanan. Walaupun dalam paragraf ke-4 opini Fiam tertulis jika tulisan itu bukan merupakan sebuah tandingan/pembelaan terhadap PMII. Namun justru dari situlah publik langsung tahu apa motifnya, sebab intriknya jelas, Fiam ingin opini publik bergeser. Tapi menurut Hermawan, sepandai-pandai kader PMII berkelit, pasti blunder juga. Lantas, mengapa karya opini garapan sahabat Fiam santer akan cacat nalar? Mari bedah pakai pisau filsafat politik dan komunikasi milik Jurgen Habermas: The Structural Transformasion of the Public Sphere.
Sebagai manusia yang sama-sama belajar filsafat, Fiam pasti paham bahwa ruang diskursus itu tidak netral. Ya, seperti kolom opini LPM Locus, memang tidak netral dan justru tidak boleh netral. Jurgen Habbermas menggagas public sphere atau ruang publik yang sehat memiliki syarat antara lain; 1. Kesetaraan posisi bicara, 2. Argumentasi rasional bukan status atau afiliasi, 3. Keterbukaan terhadap kritik, 4. Bebas dari dominasi kuasa tersembunyi, 5. Transparansi kepentingan. Kecacatan logika terjadi ketika teks menyimpang dari rasionalitas komunikatif dan jatuh pada rasionalitas strategis (membela posisi, meredam kritik, dan menjaga dominasi). Lalu apa kaitannya dengan opini Fiam? Yuk kita baca ulang dan kuliti tiap paragrafnya!
Paragraf 1-2 (Menyebut : opini LPM Locus dan tudingan terhadap PMII). Kecacatan pertama dengan gamblang terlihat maksud Fiam mereduksi persoalan struktural menjadi persoalan sumber tunggal. Fiam menyiratkan bahwa tudingan LPM Locus lemah karena bersumber dari “seorang narasumber” dan “satu tangkapan layar”. Padahal, dalam ruang publik, indikasi awal sah untuk diperdebatkan dan diskusi publik tidak sama dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, Fiam menggeser standar diskursus publik jadi standar pembuktian legal yang terlalu tinggi dan melumpuhkan diskusi. Ini bentuk rasionalitas strategis menaikkan ambang bukti untuk menggugurkan isu sebelum diuji. cukup masuk akal untuk mengabaikan fungsi ruang publik sebagai arena pengujian klaim, bukan penghakiman awal.
Dalam kacamata Habermasian, alih-alih mendorong diskursus, paragraf ini membangun defensif framing. Tujuannya jelas, yakni menyiapkan pembaca untuk meragukan kritik sejak awal, bahkan sebelum argumen diuji. Karena, diskursus rasional seharusnya dimulai dari klaim-argumen-pengujian, bukan klaim-siapa yang tersinggung. Saya curiga dari awal sahabat Fiam memang tidak membedah argumen LPM Locus, tetapi langsung menekankan bahwa opini tersebut “menyinggung” dan “menyebut PMII”. Fokus pun berpindah dari substansi ke objek yang dituduh. Ini adalah distorsi awal ruang publik, ketika ruang publik direduksi jadi arena sensitivitas, bukan pengujian kebenaran.
Paragraf 3 (Pengakuan sebagai anggota PMII dan pengalaman pribadi). Cacat nalar selanjutnya adalah otoritas subjektif, yaitu ketika pengalaman pribadi dijadikan legitimasi epistemik. Dalam status keanggotaan atau senioritas tidak memberi bobot argumen, begitupun identitas pembicara tidak menentukan nilai argumentasi. Artinya, klaim bisa diuji siapapun. Ini merupakan pergeseran rasionalitas komunikatif ke otoritas identitas, efeknya merubah ruang publik menjadi ruang kesaksian personal bukan ruang rasional.
Paragraf 4 (Klaim “bukan pembelaan” , ajakan mengesampingkan stigma). Kontradiksi performatif adalah cacat logika dalam paragraf ini. Mengklaim netral dan tidak membela, tetapi meminta pembaca mengesampingkan stigma tapi mendefinisikan kritik sebagai stigma, sekaligus memposisikan kritik sebagai emosional. Mahzab habermasian menyebut gejala ini sebagai ciri insencere speech act (komunikasi yang tidak tulus), sebab posisi kuasa disembunyikan-klaim netral dipakai jadi tameng. Akibatnya, diskursus menjadi timpang karena kepentingan tidak diungkap. Klaim objektivitas dipakai untuk menormalkan posisi dominan.
Paragraf 5-6 (Pengakuan krisis internal PMII tapi menolak kritik eksternal). Strategi klasik dengan mengakui kesalahan kecil untuk menutup kritik besar. Fiam mengakui “krisis”, tetapi hanya sebatas moral kader tidak menyentuh struktur kuasa. Dengan demikian, diskursus diarahkan agar aman bagi dominasi, bukan korektif. Kecacatan lain pada dua paragraf ini adalah standar ganda legitimasi, di mana sahabat Fiam menyebut kritik internal itu sehat (konstruktif) dan kritik eksternal sebagai “tuduhan miring”. Ini melanggar prinsip ruang publik, argumen dinilai dari isinya, bukan dari siapa yang menyampaikanya. Ruang publik mensyaratkan inklusivitas diskursus; menutup kritik eksternal sama dengan privatisasi kebenaran. Sahabat Fiam seolah memperlakukan PMII sebagai ruang semi-tertutup, bukan aktor publik.
Paragraf 7 (soal keterbukaan kompetensi dan tidak ada yang berani). Kecacatan berikutnya merupakan common mistake dari pemikir patriarkal, yakni victim-blaming struktural, di mana ketimpangan akses dibingkai sebagai “kurangnya keberanian mahasiswa lain”. Dalam wacana habermas, ini merupakan bentuk naturalizasion of domination. Artinya, struktur kuasa dianggap netral dan ketimpangan disalahkan ke individu. Ketika ketakutan mahasiswa lain dianggap alasan personal, bukan akibat dari struktur. Dengan demikian, ruang publik gagal mengenali ketimpangan sistemik.
Paragraf 8 (Strategi PMII dianggap wajar dan normal). Sampai paragraf delapan, sepertinya saya semakin mengerti konstruksi berpikir sahabat Fiam, pragmatis. Pola-pola dalam argumen selalu sama menggeser ruang publik dari komunikatif menjadi instrumental. Padahal, ruang publik tidak sama dengan arena taktik kekuasaan. Intisari dari paragraf ini adalah normalisasi rasionalitas yang strategis sekaligus menjadi kecacatan dalam membangun nalar. Ketika diskursus kampus direduksi menjadi “pertandingan strategi”. Miris ketika politik kampus dipahami sebagai “siapa paling siap strategi”. Menang lebih penting daripada argumentasi, kekuasaan lebih penting daripada legitimasi. Diskursus mati, yang hidup hanya taktik. Ini yang disebut Habermas sebagai kolonialisasi ruang publik oleh logika instrumental.
Paragraf 9-10 (Minim pemahaman demokrasi mahasiswa – tidak ada yang menantang PMII). Jujur, bagian ini merupakan favorit saya. Selama menjalani hidup jadi mahasiswa, saya selalu memegang teguh apa yang dikatakan oleh Tan Malaka jika pendidikan itu berguna untuk memperkuat tekat, mempertajam pikiran, dan memperhalus perasaan. Dan membaca paragraf ini membuat saya bertanya ulang: apakah pendidikan itu hanya legitimasi atas ketidakbecusan membangun moral? Oke, kita intip celah logikanya. Habermas mengusut akar yang menjadi tautan ruang publik yang sehat, termasuk kesetaraan bicara. Sedangkan Fiam melanggarnya dengan memposisikan PMII sebagai entitas yang lebih paham dan lebih dewasa, sementara mahasiswa lain dianggap tidak kompeten. Secara tidak langsung menciptakan hierarki epistemik (elitist framing). Logical error tidak berhenti disitu. Dengan mempertanyakan, “Siapa berani menggagalkan strategi PMII?”, dengan sendirinya mempersempit diskursus menjadi kompetisi kuasa, seolah hanya ada “tanding strategi atau diam” (false dilemma). Kritik argumentatif bukanlah tanda kelemahan, tapi mekanisme demokratis.
Paragraf 11-12 (Klaim tidak kompeten bahas KIP, Bukti dianggap tidak cukup). Saya mulai dengan tertawa, karena ini yang paling lucu. Dalam teori Habermas, ketika klaim dibuat tanpa otoritas epistemik, tetapi tetap diarahkan. Inilah yang disebut self-disqualification paradox. Mengaku tidak kompeten tapi tetap menyimpulkan tudingan lemah. Fiam menuntut bukti sempurna sebelum diskusi publik dimulai, padahal ruang publik berfungsi menguji dugaan awal, bukan menutupnya. Artinya, ia bermaksud menutup diskusi sebelum dibuka (premature closure). Ingatlah sahabat Fiam, ruang publik ada untuk menguji dugaan, bukan membungkamnya.
Paragraf 13 (Meragukan kapasitas LPM Locus). Saya tidak menyangka orang bisa terjebak cacat logika yang satu ini, mengingat Ad Hominem Institusional umum diajarkan di kelas-kelas filsafat. Kritik diarahkan pada kredibilitas media, bukan argumen, merupakan distorsi komunikasi klasik untuk melemahkan medium ruang publik, bukan memperbaiki diskursus. Tendensinya adalah merusak infrastruktur ruang publik. Fiam boleh ragu dengan apapun, tapi jangan menepis argumennya hanya karena kita bicara soal substansi bukan instansi. Dan sedikit saran dari sahabatmu ini, bedakan opini dan reportase biar kamu tidak kebanyakan nge-jokes saat berargumen di ruang publik. Karena kamu terus mereproduksi konsep yang keliru, jadi saya anggap bukan sekedar slip of tongue atau typographycal error, melainkan slip of logic.
Paragraf 14-16 (ajakan tabbayun, anti ngrasani, harmoni). Moralisasi perdebatan adalah cacat nalar lain dari rentetan daftar gagal nalar opinimu. Di buku yang sama, Habermas menolak konsensus palsu, konflik argumentatif justru esensi ruang publik yang sehat. Kritik diposisikan sebagai konflik yang tidak dewasa dan harmoni, dijadikan sebagai standar etis tunggal. Melihat konstruksi kalimat antar paragraf 14-16, saya ingin tanya sama sahabat Fiam. Secara normatif, emang manusia bisa memutar wacana tanpa rasan-rasan?
Paragraf 17-18 (penutup normatif dan generalisasi anomali). Terakhir adalah sesat pikir atau generalization reversal adalah sebuah inkonsistensi logis dalam menyusun sebuah opini argumentatif. Menolak generalisir PMII, tapi sebelumnya mengeneralisasi kritik sebagai emosi, stigma dan ngrasani.
Dalam uraian analisa saya, tentu menggunakan pendekatan Habermasian. Dapat pembaca simpulkan dengan jernih dan dewasa seperti kata sahabat Fiam, bahwa keseluruhan teks opini memang tidak berupaya memperluas perspektif atau jangkauan ruang publik, tetapi untuk menjinakannya. Mengapa? Sederhana saja, karena didominasi rasionalitas strategis, menyamarkan relasi-kuasa, privatisasi kritik struktural, menggeser ruang publik menjadi arena stabilisasi kuasa, dan mengutamakan harmoni semu daripada diskursus terbuka.
Alih-alih menyajikan poin, sahabat Fiam terlihat sebagai pion dalam wacananya sendiri. Padahal, dari membaca judulnya saja, saya sebagai pembaca sempat menaruh ekspektasi: wah, ternyata sahabat Fiam mampu membahasakan tanggapan atas kritik yang dilontarkan publik kepada organisasi yang dianutnya secara metaforis “menanggalkan atribut”, yang saya terima sebagai simbol melunturkan persepsi ke-akuan. Namun, tidak apa-apa, ekspektasi biarlah menjadi ekspektasi. Lagipula, ini bukan kali pertama saya digocek judul.
Opini “Menanggalkan Atribut Biru Kuning”, yang ditulis fiam menunjukkan tiga implikasi besar atas diri PMII sebagai organisasi dan penulisnya sebagai kader. Pertama, sahabat Fiam gagal paham substansi ruang publik dan diskursus lintas wacana. Kedua, PMII (UIN) gagal membentuk kader yang mengedepankan etik dan akal dalam berpolitik. Ketiga, PMII sukses menambal semua kekurangan itu dengan surplus kepercayaan diri bagi mayoritas kadernya, termasuk sahabat saya: Muhammad Fiam Setyawan.
Sebagai epilog untuk opini balasan ini, saya ingin membalik penyataan sahabat Fiam di paragraf akhir “malu-malu untuk mengenal PMII”. Saya rasa tidak demikian, tapi dengan konstruksi pikiran seperti itu yang membuat kesan PMII malu-maluin. Dengan sepenuh hati, saya ingin sahabat saya, Fiam, atau kader-kader PMII lainnya, secara radikal berbenah dari akal, hati, sampai perbuatan. Tinggalkan rayon, datangi akal! Salam pergerakan!
Penulis: Muhammad Hermawan Sutanto
Editor: Chandra



