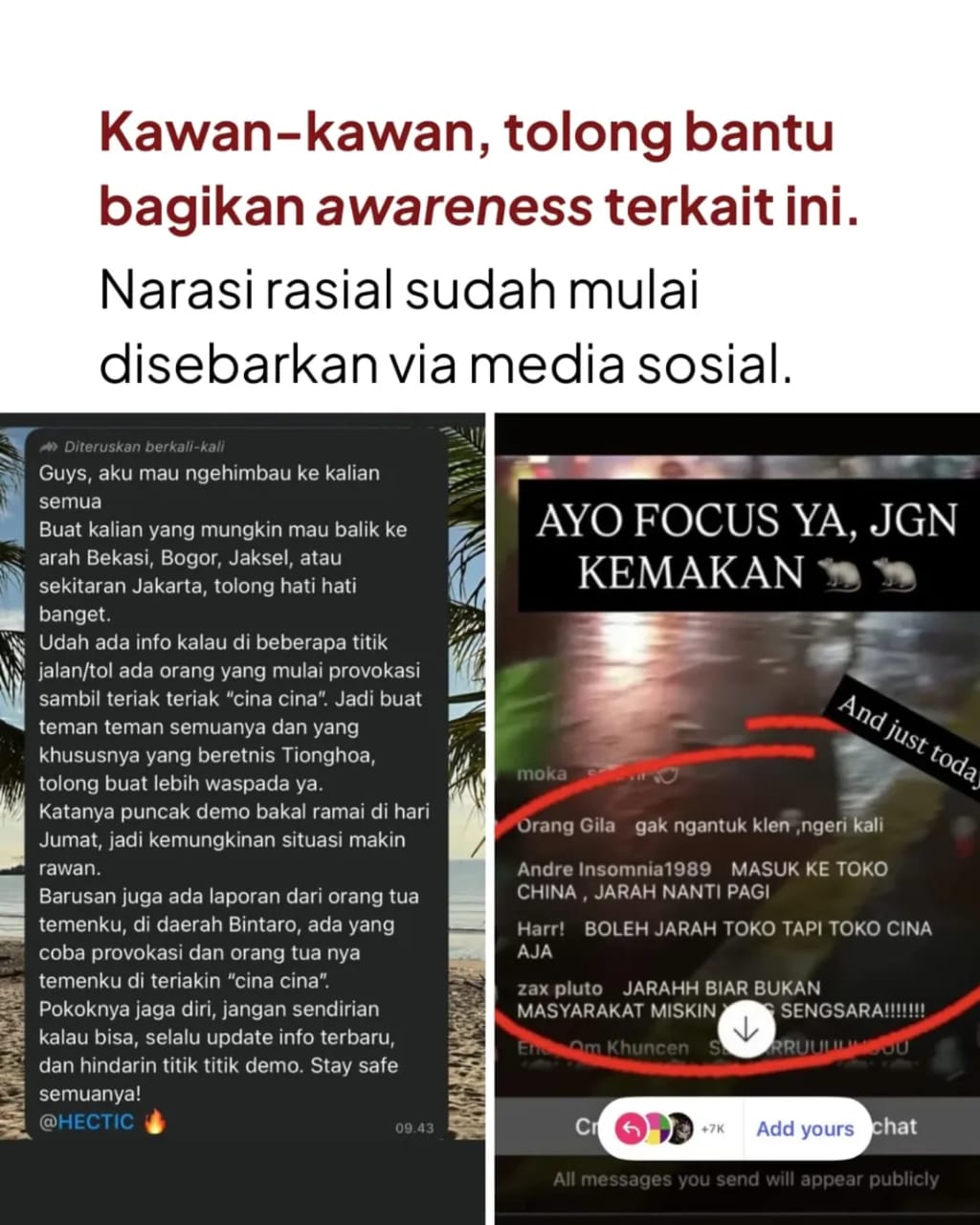Ilustrasi dibuat menggunakan artifisial intelejen dengan prompt”ilustrasi politik balas budi” oleh Hasbi Muhamad
Dalam kontestasi politik, dukungan tidak ada yang gratis, ada tenaga, uang, dan loyalitas yang harus dipertaruhkan. Persoalannya muncul apabila kekuasaan yang diraih diperlakukan sebagai alat untuk membayar kembali jasa para pendukung. Inilah yang kerap disebut politik balas budi, rasa terimakasih tidak berhenti pada ucapan melainkan menjelma menjadi sumber daya dan jabatan.
Praktik ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang secara tidak langsung menstigmatisasi wujud selamat atau rasa terima kasih tidak hanya sebatas sebagai perkataan. Dalam tradisi rewang orang-orang yang telah membantu untuk menyukseskan acara tuan rumah umumnya akan mendapat upah makanan atau barang sebagai bentuk terima kasih atas andil yang mereka berikan. Namun, balas budi dalam rewang jauh berbeda dengan balas budi dalam kenegaraan. Sebab dalam arena kekuasaan, hal ini dinilai bukan sebagai tanda terima kasih atas moral antar individu tapi sebagai transaksi antar elit politik.
Ketika balas budi yang bersifat moral bergeser makna menjadi alat penukaran dalam arena politik, hal tersebut secara tidak langsung memaksa para kandidat politik mencari berbagai jalan untuk mendapatkan dukungan finansial, sayangnya jalan yang ditemui sering kali tidak sebaik yang terlihat. Salah satunya adalah melalui “open booking jabatan”, dimana bangku-bangku strategis ditawarkan sebagai “hadiah” yang akan didapatkan bagi para pihak atau kelompok yang ingin memberikan dukungannya. Lebih jauh, gelombang ini juga menargetkan dominasi kelompok sipil, lewat PP Nomor 25 Tahun 2024, pemerintah secara resmi memberi akses organisasi kemasyarakatan agama untuk mengelola tambang. Langkah tersebut juga menegaskan bahwa meritokrasi masih terkubur dalam di negeri ini.
Akibat orientasi elit politik yang mengutamakan loyalitas, metode ini perlahan mengaburkan garis antara kepentingan publik dan kepentingan individu, akan tetapi sering kali dianggap wajar berkat tidak adanya aturan yang melarang secara eksplisit. Selain itu cara ini dianggap salah satu bentuk politik praktis yang “normal” dalam demokrasi, sehingga berbagai pendekatan dihalalkan selagi tidak menyalahi aturan formal. Lantas, praktik yang dianggap normal ini sebenarnya menguntungkan siapa?
Logika mereka yang mengaburkan kepentingan publik ini berdampak langsung pada kebijakan yang acap kali menempatkan masyarakat sebagai pihak yang diuntungkan, namun, pada realitanya merupakan korban dari mereka yang mencari keuntungan. Mencanangkan pentingnya kualitas hidup sehat, seraya menonaktifkan jutaan peserta BPJS Kesehatan PBI, adalah punchline yang tak tertebak dari para komedian politik ini. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya siapa yang perlu diobati? rakyat atau akal mereka?
Sebagai negara penganut demokrasi, para elit politik seharusnya sadar bahwa kekuasaan yang mereka dapatkan merupakan sebuah titipan dari rakyat dan harus untuk kepentingan rakyat. Namun, dalam implementasi justru malah mencederai konstitusi. Melalui fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, negara hadir bukan melalui pintu tiap-tiap rumah, melainkan hanya “atap”, seolah hak asasi manusia bukan lagi menjadi tujuan, melainkan sekedar pilihan.
Dengan demikian, tanpa disadari balas budi, dalam hal politik, adalah ancaman nyata bagi bangsa. Menilai ulang praktik ini adalah langkah pertama bertransformasi agar balas budi tetap menjadi balas budi bukan sampul untuk mengikis demokrasi.
Penulis: Hanan
Editor: Hasbi