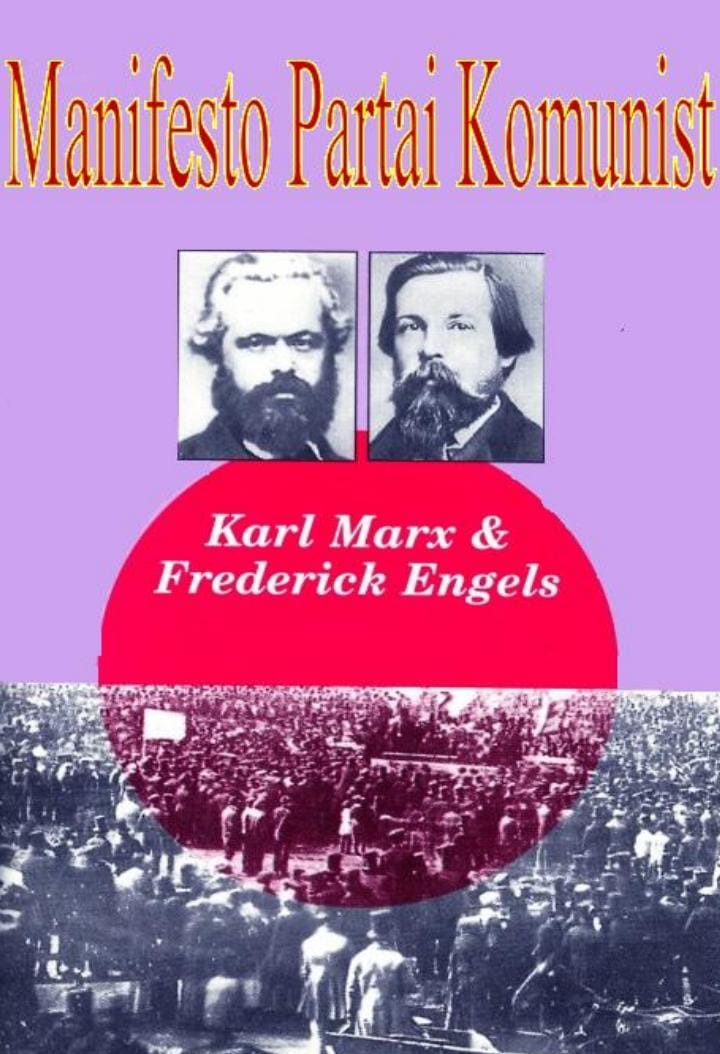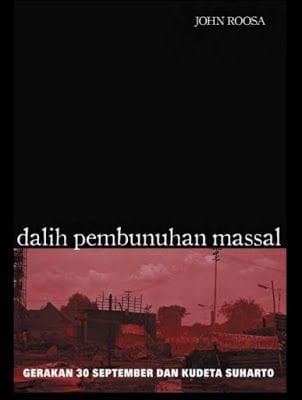Gambar diambil dari pinterest
Judul Buku : Raja Limbung: Seabad Perjalanan Sawit di Indonesia
Penulis : Mardiyah Chamim, Dwi Setyo Irawanto, Yusi Avianto Pareanom, Zen Hae, Irfan Budiman
Isi : xiv + 244 halaman, 16 x 24 cm
ISBN : 978-602-19607-0-7
Penerbit : Sawit Watch dan Tempo Institute
Cetakan : Pertama, April 2012
Raja Limbung bukan sekadar buku tentang sawit, melainkan sebuah dakwaan terhadap cara negara memperdagangkan masa depan publik demi statistik pertumbuhan. Dengan menelusuri satu abad perjalanan industri sawit, buku ini memaksa pembaca melihat bahwa di balik devisa, sertifikasi, dan jargon pembangunan, tersimpan sejarah panjang perampasan ruang hidup, pembungkaman warga, dan pembiaran kerusakan ekologis. Ulasan ini tidak bermaksud menempatkan sawit sebagai musuh tunggal, tetapi menguji satu pertanyaan yang lebih mengganggu: ketika kebijakan komoditas terus diproduksi tanpa akuntabilitas publik, siapakah yang sesungguhnya dilindungi negara?Rakyatnya atau kepentingan yang tak pernah ikut menanggung akibatnya?
Berangkat dari pertanyaan itu, Raja Limbung disusun bukan sebagai laporan netral, melainkan sebagai peta tuduhan. Buku ini bergerak sistematis dari hulu wacana pembangunan hingga ke hilir penderitaan warga, seolah hendak menunjukkan satu hal: kerusakan yang terjadi bukan akibat kelalaian, melainkan akibat pilihan kebijakan yang disengaja dan dipelihara.
Pertama, buku ini membuka dengan membongkar mitologi sawit sebagai penyelamat ekonomi nasional. Sawit dipuja sebagai mesin devisa, penyerap tenaga kerja, dan simbol kemandirian ekonomi. Namun Raja Limbung menelanjangi ilusi tersebut dengan menunjukkan bahwa keberhasilan makroekonomi dibangun lewat penghapusan ongkos sosial dari neraca negara. Tanah yang dirampas, sungai yang rusak, dan kehidupan warga yang tercerabut tidak pernah dicatat sebagai kerugian publik. Ia dianggap harga yang wajar demi pertumbuhan. Di sini, sawit tampil bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai alat pembenar pengorbanan sistematis.
Kedua, buku ini menelusuri sejarah sawit untuk menegaskan bahwa konflik hari ini bukan kecelakaan administratif, melainkan warisan politik yang tidak pernah diputus. Dari kolonialisme hingga Orde Baru, dari sentralisasi hingga desentralisasi, pola dasarnya tetap sama: konsesi besar, pengambilan keputusan tertutup, dan warga yang dipaksa menyesuaikan diri dengan peta yang tak pernah mereka buat. Reformasi, dalam narasi buku ini, gagal menjadi koreksi; ia justru memperbanyak aktor yang bisa memperjualbelikan izin atas nama pembangunan.
Ketiga, Raja Limbung masuk ke inti persoalan: tata kelola perizinan yang sengaja dibiarkan keruh. Tumpang tindih HGU, kawasan hutan, dan wilayah adat bukan sekadar kekacauan birokrasi, melainkan ruang abu-abu yang menguntungkan pemilik modal. Dalam kondisi hukum yang kabur, negara cenderung memilih jalan termudah: menertibkan warga, bukan menertibkan izin. Buku ini dengan gamblang menunjukkan bagaimana hukum berubah dari alat perlindungan publik menjadi instrumen disiplin terhadap korban.
Keempat, buku ini membedah dampak sosial dan ekologis sawit sebagai konsekuensi politik, bukan bencana alam. Banjir, kekeringan, hilangnya pangan lokal, dan rusaknya ekosistem diposisikan sebagai akibat langsung dari keputusan membuka lahan tanpa menghitung daya dukung. Dengan kerangka ini, Raja Limbung mengajukan tuduhan serius: negara telah gagal menjamin hak dasar warga atas air, pangan, dan keselamatan hidup, lalu menyamarkannya sebagai risiko pembangunan.
Kelima, buku ini menelanjangi industri pencitraan keberlanjutan. CSR, sertifikasi, dan jargon hijau dipresentasikan sebagai kosmetik kebijakan—ramah di brosur, rapuh di lapangan. Alih-alih menyelesaikan konflik, skema ini justru berfungsi meredam kemarahan publik dan memberi alibi moral bagi praktik lama. Sertifikasi tidak dipersoalkan karena kurang sempurna, tetapi karena ia tidak menyentuh akar masalah: ketimpangan kuasa antara warga dan korporasi.
Pada bagian akhir, Raja Limbung menyodorkan rekomendasi—transparansi, pengakuan hak adat, pemulihan ekologis—namun nada pesimisme tetap terasa. Bukan karena solusi tak tersedia, melainkan karena kehendak politik untuk melindungi kepentingan publik terus ditunda. Dengan demikian, buku ini menempatkan sawit sebagai cermin paling jujur dari negara hari ini: kuat dalam mengatur angka, lemah dalam menjaga manusia.
Dibaca secara utuh, Raja Limbung bukan sekadar kritik terhadap industri sawit, melainkan tuduhan terhadap model pembangunan yang menormalisasi pengorbanan publik. Ia memaksa pembaca bertanya, dengan nada yang tak nyaman: jika pembangunan terus dijalankan dengan cara ini, siapa lagi yang akan dikorbankan setelah tanah, air, dan kehidupan warga dianggap habis pakai?
Marginalia
Saya membaca Raja Limbung dengan simpati, tetapi tidak dengan kepatuhan. Buku ini menggugah, marahnya terasa sah, dan keberpihakannya pada korban patut dihormati. Namun justru karena ia mengklaim berbicara atas nama kepentingan publik, buku ini harus diuji lebih keras daripada sekadar dipuji. Keberpihakan tidak otomatis menjadikan argumen kebal kritik.
Kelemahan utama Raja Limbung, bagi saya, terletak pada kecenderungannya mengganti ketelitian dengan keyakinan moral. Banyak tuduhan struktural disampaikan dengan nada pasti, tetapi tidak selalu ditopang oleh bukti yang cukup untuk menutup ruang sangkal. Dalam medan kebijakan publik yang keras, kebenaran etis saja tidak cukup; ia harus disertai presisi data. Tanpa itu, kritik yang seharusnya memaksa perubahan justru berisiko dipinggirkan sebagai suara emosional.
Saya juga melihat buku ini terlalu nyaman menggunakan kasus-kasus paling gelap sebagai representasi keseluruhan. Luka memang perlu diperlihatkan, tetapi ketika luka dijadikan wajah tunggal, kompleksitas hilang. Tidak semua praktik persawitan bekerja dengan pola yang sama, dan dengan mengabaikan variasi tersebut, buku ini justru melemahkan kemampuannya sendiri untuk menawarkan koreksi kebijakan yang tajam dan terarah.
Masalah lain yang mengganggu adalah cara “negara” diperlakukan sebagai sosok raksasa tanpa anatomi. Negara disalahkan—dan sering kali memang layak disalahkan—tetapi tanpa pembedaan peran dan tanggung jawab institusional. Akibatnya, kemarahan publik menjadi luas, tetapi tuntutan politik menjadi kabur. Kritik yang baik seharusnya mempersempit sasaran, bukan sekadar memperbesar amarah.
Saya sepakat dengan kecurigaan buku ini terhadap sertifikasi dan CSR, tetapi saya tidak puas dengan caranya berhenti di tingkat niat buruk. Tanpa pengujian berbasis hasil, penolakan terhadap sertifikasi terdengar seperti penutupan pintu, bukan pembongkaran sistem. Bagi saya, kritik yang paling berbahaya adalah kritik yang menolak kemungkinan perbaikan tanpa terlebih dahulu mengujinya.
Namun semua kelemahan itu tidak membuat Raja Limbung menjadi buku yang gagal. Ia gagal sebagai panduan teknokratis, tetapi berhasil sebagai gangguan politik. Buku ini memaksa pembaca berhenti percaya bahwa pembangunan selalu netral dan kebijakan selalu rasional. Ia membuat ketidakadilan terasa personal, bukan statistik.
Saya tidak membaca Raja Limbung untuk mencari jawaban akhir, melainkan untuk mempertajam kecurigaan. Dan dalam hal itu, buku ini bekerja dengan baik. Ia mengingatkan saya bahwa kepentingan publik sering kali dikalahkan bukan oleh niat jahat semata, melainkan oleh kebijakan yang terlalu percaya diri pada angka dan terlalu abai pada manusia.
Penulis: Muhammad Hermawan Sutanto
Editor: Abril