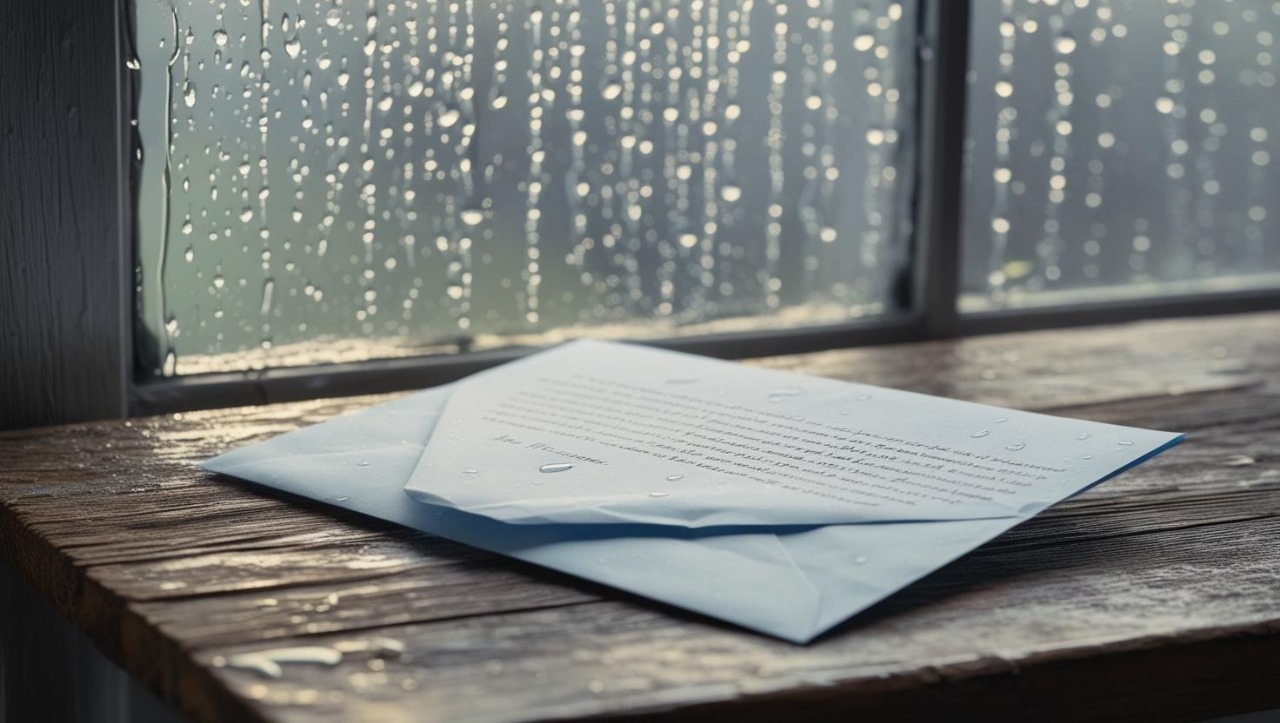Sumber gambar: https://pin.it/5ISCHVzLJ
Aku sering mendengarkan cerita dari ibuku bahwa dunia itu sangatlah berwarna. Beliau adalah seorang seniman dan selalu mengekspresikan keindahan melalui lukisannya. Aku hanya tinggal bersama ibu di tempat yang gelap ini, tetapi aku tidak pernah merasakan kedinginan. Kehangatan yang ibu berikan dapat aku rasakan dengan nyaman walaupun aku tidak begitu mengerti bagaimana perasaan ibu sebenarnya.
“Assalamualaikum!” itu suara tetanggaku, Bu Diah, dan sepertinya dia datang bersama putri bungsunya, Ratih. Beliau memang sering berkunjung ke kediamanku untuk menjagaku di rumah selagi ibuku banting tulang di kota, tetapi ini kali pertama aku bertemu Ratih. Ia sangat cantik, seperti yang aku bayangkan.
“Galih, kenalin ini anak saya, Ratih, yang sering saya ceritakan sama kamu. Bagaimana menurutmu? Cantik bukan? Hahaha,” canda Bu Diah yang membuat Ratih yang tersipu malu.
“Maaf Lih, saya tinggal dulu sebentar soalnya ada rapat RT di balai desa. Makanya saya bawa anak saya untuk menemani kamu di rumah. Ratih, tolong temani Galih dan bersenang-senanglah sama Galih!” pesan Bu Diah sembari mengusap kepala Ratih.
Setelah beliau pergi, Ratih langsung mengajakku mengobrol. Sudah lama sekali aku tidak mengobrol dengan orang seumuranku, apalagi lawan jenis. Terakhir yang kuingat diriku hanya mengobrol dengan teman imajinasiku saja.
Sudah tiga hari dari waktu terakhir kali kita bertemu, Ratih tidak pernah datang lagi. Bu Diah bercerita bahwa Ratih sedang sakit, tapi tidak menceritakan apa penyakitnya dan berkata bahwa Ratih akan bermain denganku lagi setelah sehat.
Aku sangat senang ketika bertemu dan bercerita dengan Ratih. Hidupku yang membosankan rasanya telah berubah. Kurasa, aku telah menyukai si Ratih.
“Bu, ayo kita bertamu ke rumah Bu Diah sekali-sekali!” ajakku pada ibu yang sedang menyetrika bajuku.
“Besok,ya, Lih pas waktunya Ibu libur.”
“Asikkkk!” kata dalam hatiku yang senang karena pada akhirnya aku akan bisa bertemu Ratih lagi. Ibuku menepati janjinya. Setelah 4 hari, kita akhirnya pergi ke pemakamannya. Ya benar, Ratih meninggal.
“Bu Diah, apa yang terjadi?. Penyakit apa yang diderita si Ratih? Bukankah Bu Diah bilang Ratih akan sembuh?” tanyaku tanpa rasa bersalah setelah dari pemakamannya.
Aku baru sadar bahwa diriku sangat bodoh karena mempertanyakan hal itu tanpa memahami situasinya. Andai saja aku bisa membaca perasaan Bu Diah sebagai ibu kandung Ratih dan mengontrol emosiku. Tentu saja Bu Diah disini yang merasa paling terpukul karena telah kehilangan darah dagingnya.
Pada akhirnya, Bu Diah bercerita kepadaku. “Nak Galih, maaf, ya, sini ibu ceritain. Sebenarnya…..” suara gemetar Bu Diah membuatku merasa sangat bersalah. Aku seharusnya tidak terburu-buru dan membiarkannya beristirahat terlebih dahulu.
Setelah mendengar cerita Bu Diah, ternyata perkara sakitnya Ratih adalah kebohongan. Ratih sebenarnya waktu itu menghilang, dan ia meninggal bukan karena penyakit yang dideritanya.
“Aku mendengar kabarnya saat sedang sholat subuh, nak. Ibu senang mendengar Ratih ditemukan, tapi ketika diberitahukan kondisinya , ibu tak kuasa menahan tangis sampai merasa tidak mendengar suara apapun lagi. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan bahwa Ratih meninggal karena bunuh diri.”
Begitu mendengar cerita itu aku menangis, dan dadaku terasa sangat sesak hingga terasa sulit untuk bernafas. Aku pikir semua ini salahku, seharusnya waktu itu aku menjawab pertanyaannya dengan hati-hati. Aku sungguh tidak mengira bahwa jawabanku waktu itu bisa mengakhiri hidup orang yang sangat berharga bagiku. Seharusnya aku tau bahwa jawabanku sangat berarti bagi Ratih. Karena kita memiliki kesamaan.
Setelah kepergian Ratih, aku terus berada di kamar. Padahal Bu Diah tetap datang untuk menemaniku setelah kepergian si Ratih. “Galih, ayo makan! Sudah waktunya, nak, jika kamu nggak mau bertemu saya dulu karena teringat Ratih, biar nanti ibu keluar dulu. Galih yang penting makan dulu, tidak usah pikirin ibuk dulu. Makanannya ada di meja makan ya,” panggil Bu Diah yang khawatir denganku.
Maafkan aku, Bu Diah. Aku hanya merasa bersalah sehingga tidak berani bertemu dengan Bu Diah. Aku tidak menceritakan apapun kepada Bu Diah karena aku takut belaiu akan membenciku.
Sampai sekarang aku masih ingat obrolanku dengan Ratih waktu itu. Aku tidak pernah melupakannya. Karena itu pertama kalinya aku memperdulikan orang lain.
“Galih, menurutmu aku orang yang seperti apa?” tanya Ratih pada waktu itu.
“Menurutku, kamu seperti kucing bagiku. Kucing tidak peduli bagaimana diriku, tapi mereka selalu mendengarkan aku. Dan yang pasti kucing itu sangat lucu dengan bulu-bulunya yang halus. Eh tapi aku ini cuma perumpamaan, ya, hahaha. Bukan berarti aku menyamakanmu dengan hewan,” jawabku sambil tertawa
“Hahaha aku juga paham, kok. Kucing itu memang hewan yang lucu, ya. Terimakasih telah menghiburku. Tapi sebenarnya aku bahkan jauh berbeda dari perumpamaan kucing yang lucu.”
Tawa Ratih membuatku tersenyum. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah serius. “Lih, apakah kamu pernah dibully atau diejek?” tanyanya.
“Pernah,” jawabku sambil mengingat kenangan suram masa laluku. Aku dulunya sering dibully, bahkan sampai pernah ditendang dan dihajar. Itu rasanya benar-benar sakit, dan menyisakan trauma yang sangat mendalam hingga membuatku tidak berani bersekolah lagi. Walaupun akhirnya murid yang merundungku dikeluarkan dari sekolah, namun aku masih merasakan ketakutan. Suasana di kelas mungkin tidak cocok untukku, karena semuanya tidak menyukaiku.
“Kita memang sama, kita punya cerita yang tidak ingin kita ingat kembali. Kupikir jika aku tidak menyerah semuanya akan berubah. Namun ternyata sama saja, aku terus dibully. Aku lelah, aku tidak ingin seperti ini. Aku juga ingin diperlakukan normal,” ujar Ratih sambil menangis tersedu-sedu.
“Itu berarti kamu orang yang kuat, Ratih. Kamu terus menghadapi masalahnya, tidak sepertiku yang memilih kabur. Bahkan aku dulu berpikiran untuk melarikan diri dari dunia ini. Aku sempat ingin bunuh diri karena menurutku semuanya percuma, lingkungan sosial tidak cocok untuk orang sepertiku,” kataku untuk menyemangati Ratih.
“Aku pikir itu titik terendahku, tapi ternyata ada yang lebih rendah,” lanjutku
“Memangnya apa yang lebih rendah?” tanya Ratih penasaran.
“Suara Janggar di pemilihan ketua RT kemarin,” candaku untuk mengembalikan suasana yang menyenangkan.
“Hahahaha!” Kita berdua tertawa lepas seperti melupakan pembicaraan menyedihkan sebelumnya. Kupikir setelah itu Ratih kembali percaya diri. Aku pun mengira bahwa Ratih tidak kembali lagi karena telah menemukan jati dirinya kembali. Ternyata aku salah.
“Nak, ayo bangun, sudah subuh. Waktunya sholat, cepat ambil wudhu,” suara ibu membangunkanku dari mimpi. Aku tertidur cukup lama hingga lupa memakan masakan dari Bu Diah. Aku bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat, serta tak lupa berdoa untuk dipermudahkan urusanku di dunia ini.
“Nak, ayo temani ibu ke pasar. Kamu kan jarang keluar rumah,” ajak ibu setelah aku selesai melaksanakan sholat. Aku menerima ajakan ibu karena mimpi kemarin, aku harus kuat. Aku langsung bersiap-siap dan mengambil tongkatku. Kami berdua berangkat ke pasar dengan naik angkot.
Suasana pasar ramai seperti biasanya, riuh rendah dari segala arah. Dalam kebisingan pasar itu, aku mendengar lirih suara Ratih. Sepertinya aku sangat kelelahan hingga berhalusinasi, sebaiknya aku beristirahat terlebih dahulu.
“Bu, aku capek. Aku mau istirahat di taman dulu ya.”
“Tunggu bentar ya, Lih. Gak lama kok, tinggal sedikit lagi waktumu.” Perkataan ibu membuatku bingung. Apa maksudnya waktuku tinggal sedikit.
Aku duduk di bangku taman, dibawah pohon mangga. Tiupan angin membawa daun dan diriku dengan tenang. Aku termenung, salah satu ucapan dari Ratih terbayang-bayang dalam pikiranku. “Menurutmu, aku yang tidak mampu berjalan ini apakah ada tempat untuk hidup hingga bisa tertawa lepas? Apakah karena aku cacat, aku tidak boleh menikmati hidup?”
Aku paham, kita sama. Tapi, aku kalah. Aku yang pernah berusaha untuk lari tentu kalah. Bagaimanapun kita melawan, kitalah yang tertindih. Apakah ini hukum alam? Apakah ini takdir? Apakah ini memang jalan cerita penyandang disabilitas?
Aku mendongak, segalanya berputar cepat. Tunggu, seharusnya aku tidak berada di sini. Apakah segalanya tadi hanyalah mimpi? Tiba-tiba semuanya terasa berbeda, apakah tadi itu adalah kilas balik diriku sebelum menghadap Tuhan?
Aku tersadar dan langsung berusaha mengucapkan kata-kata agar terdengar oleh orang di sekitarku. “Galih, kamu udah sadar?” tanya ibuku sambil menitikkan air mata.
“Dokter! Suster! Oh iya, seharusnya aku menekan tombolnya agar dokter datang,” kata Ibu dengan panik.
“Bu, dengarkan Galih sebentar ya,” ujarku lemah.
“Galih minta maaf karena dulu sempat ingin bunuh diri. Galih minta maaf jika selama hidup ini Galih terus membuat kesulitan Ibu kesulitan. Juga, Galih ingin sekali melihat lukisan terbaik dari Ibu yang pernah Ibu ceritakan. Aku juga menitipkan maaf untuk Bu Diah karena Ratih bunuh diri mungkin karena pernah salah memahami ceritaku atau karena omonganku,” aku berusaha mencari dan memegang tangan ibuku. Aku rasa waktuku tinggal sedikit. Terdengar suara orang-orang berlari hendak ke ruanganku.
“Seharusnya Ibu yang minta maaf, nak, Ibu seha…“ suara ibu terdengar semakin samar. Aku rasa waktuku benar-benar habis. Tapi aku sudah lega.
Aku, pemuda umur 20 tahun yang mengalami tunanetra meninggal karena dikeroyok dan dipukul dengan tangan mengepal dan balok kayu, serta ditendang-tendang seolah bukan manusia oleh delapan anak SMA. Aku yang pernah berusaha kabur dari dunia ini, aku yang trauma berat ini, akhirnya bisa memaafkan mereka yang selalu menindasku. Aku senang sekali bisa menerima diriku sebelum pergi karena mimpi yang menyenangkan itu.
Walaupun singkat dan meskipun Ratih tidak nyata. Ya benar, ibuku pernah bilang bahwa Bu Diah belum mempunyai anak karena anak pertamanya meninggal dalam kandungan dan kini anak keduanya baru akan dilahirkan. Kuharap Bu Diah akan memberikannya nama Ratih.
“Lukisan yang Ibu maksud, lukisan terindah di dunia itu adalah lukisan dirimu,”ujar Ibu yang membuatku sangat bahagia.
Aku sadar posisi kita sebagai orang disabilitas masih sulit untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial. Kita sebagai penyandang disabilitas juga tidak memilih untuk terlahir seperti ini. Maka dari itu, kita berusaha terus berjuang dan memberanikan diri. Kita ingin diperlakukan dengan layak seperti orang normal.
Penulis: Aryaseta
Editor: Abril