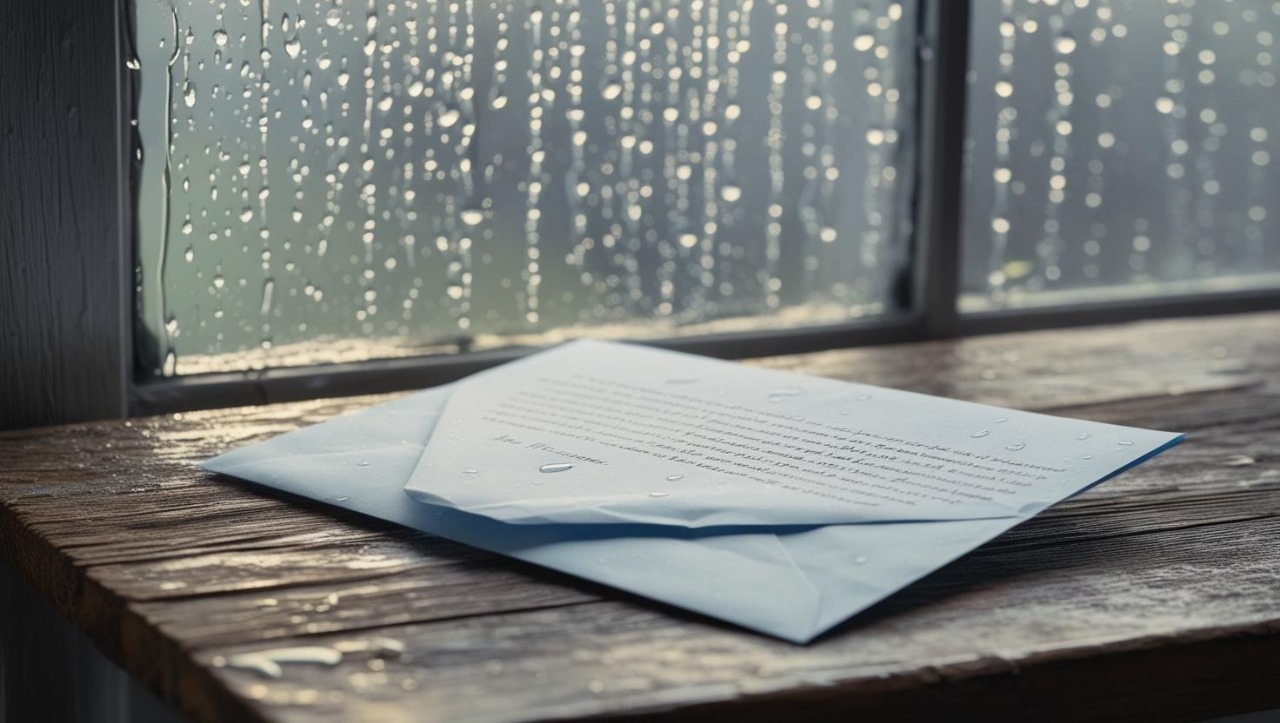“Jauh di waktu yang sudah berlalu, pada zaman disaat kalian belum dilahirkan, cerita ini dimulai. Semua kenikmatan yang kalian rasakan selama ini adalah hasil dari perjuangan orang-orang terdahulu. Merekalah yang disebut sebagai legenda. Sosok yang paling berjasa, yang patut dihormati sepanjang masa. Siapa namanya?”
Anak-anak berteriak, saling berebut ingin menjawab. Membuat istirahatku terganggu. Aku mendudukkan diri sambil menatap malas perkumpulan di depan mataku. Seorang gadis yang seumuran denganku mencoba menenangkan mereka. Aku tak ada niat untuk membantu. Lagipula, aku sudah muak dengan cerita yang dia bicarakan.
“Sekar Ratih Purbasari!” Seorang anak yang ditunjuk menjawabnya dengan penuh antusias. Senyum bahagia nampak menguar di sana. Aku pun mendengus kesal.
Sebenarnya, itu bukan cerita yang buruk. Bukan sekedar cerita yang ditulis sembarangan. Bukan pula cerita yang berasal dari khayalan. Cerita turun temurun itu berasal dari kisah nyata. Kisah seorang perempuan yang memperjuangkan haknya. Melawan para lelaki dan menegakkan diri. Membantah jika perempuan hanyalah sosok penghasil keturunan saja. Membuktikan betapa kuatnya kaum hawa.
Aku bukannya tak kagum dengan Ibu Sekar—begitu kami memanggil sang legenda—beliau adalah sosok yang hebat, menginspirasi, serta berani. Namun, ada hal lain yang membuatku geram.
“Dahimu mengerut, Fa. Kau masih benci dengan cerita itu?” tanya gadis yang telah usai bercerita. Anak-anak pun sudah pergi dari tempat ini tanpa kusadari.
“Kapan aku membencinya? Ibuku yang mengatakannya padamu?”
Lawan bicaraku justru terkekeh. Sepertinya memang benar, ibuku suka sekali menggosip. Bahkan menceritakan hal buruk tentang anaknya sendiri. Menyebalkan.
“Tuh, kau cemberut lagi. Wajahmu jadi jelek, tahu!” ingatnya sambil menarik kedua pipiku, membentuk sebuah senyuman di sana. “Tapi, tanpa Tante Siska beritahu pun, sepertinya semua orang tahu. Kau selalu berdecak ketika anak-anak memintamu bercerita. Kalau bukan benci, lantas apa?”
Kepalaku tertunduk, melepas cubitannya. “Aku hanya kesal.”
“Pada Ibu Sekar?”
Aku menggeleng, “Pada keadaan yang sekarang. Tapi, karena semua ini berkat Ibu Sekar, mungkin aku juga membencinya? Entahlah, Hani. Aku merasa hidup kita yang sekarang tak jauh berbeda dengan saat Ibu Sekar masih hidup.”
“Mana ada!” bantah Hani, “Hidup kita yang sekarang justru lebih menyenangkan! Kita bebas hidup seperti apa yang kita mau, tidak ada yang berani melakukan kekerasan, justru kita dihormati sepanjang waktu, dan yang paling penting, kedudukan kita di atas para lelaki. Hidup seperti ini impian, tahu! Mana ada wanita yang tak mau menjadi ratu? Kau ini aneh, Fa.”
“Iya, kita memang dibebaskan melakukan apapun. Tapi, kita juga tidak boleh melakukan apapun. Bekerja, memasak, bahkan belajar saja dilarang! Aku tak tahu kita sedang berada di surga atau neraka.” Aku mendengus lagi.
Hani memukul kepalaku, meski tak terasa apapun. Namun, aku tetap mengaduh. “Kau memang gila. Yang perlu kau lakukan hanyalah makan, tidur, dan rebahan! Masih saja mengeluh. Sok-sokan banget mau belajar. Sudah, hidup santai saja,” saran Hani.
“Kalau gitu, Han, sekarang aku tanya. Apa yang membuat Ibu Sekar bisa memenangkan perang dengan kaum adam?”
Gadis itu berpikir sejenak. Entah apa yang dia pikirkan hingga mata besarnya terus menyipit. “Keberanian?” tebaknya.
“Salah. Beliau memakai strategi dalam pertarungan. Apa kau berpikir jika membuat strategi itu gampang?” tanyaku lagi.
“Nggak, lah! Ibu Sekar, ‘kan, pintar.”
Akhirnya dia memahami maksudku. “Nah, dari cerita legenda itu, kita tahu jika lelaki itu memang memiliki kelebihan di fisik. Sedangkan kita, perempuan, memiliki kelebihan di otak. Tapi, jika kita saja tak menggunakan kelebihan yang kita miliki alias belajar, apalagi yang kita punya? Tidak ada, Han. Kita tidak berdaya sekarang. Kita tidak ada bedanya dengan perempuan di jaman dulu. Bodoh, bahkan aku kalah dalam hitungan tambah menambah dengan adikku,” celotehku panjang lebar.
“Tunggu, kau masih berjumpa dengan adikmu?”
Aku mengangguk sebagai jawaban. Hani segera meraih kedua bahu lantas mencengkramnya. Membuatku meringis. Belum sempat memprotes, dia melototkan mata sembari berteriak. “Kau gila, Fa! Kita dilarang bertemu lelaki. Mereka bisa mencelakaimu! Meskipun dia adikmu, dia sudah dewasa. Tidak ada jaminan dia tidak akan melukaimu. Di dalam cerita juga pernah dikatakan jika seorang saudara kandung yang memperkosa saudarinya, bukan? Jauhi adikmu, Fa. Jangan temui dia lagi. Laki-laki itu hanyalah makhluk buas yang memiliki akal!”
Aku terkejut. Perkataannya masuk ke telingaku tanpa celah. Aku tahu, dia pasti akan berkata seperti demikian. Bahkan semua wanita di sini juga berpikir yang sama.
Semuanya telah dirombak ketika Ibu Sekar berhasil memenangkan pertempuran. Beliau membuat tembok besar yang membuat batas antara lelaki dan perempuan. Perempuan diperlakukan bak ratu, sedangkan lelaki bekerja seperti budak di luar tembok. Di dalam tembok hanya ada wanita dan anak-anak. Itu pun, jika anak lelaki sudah berumur lima belas, mereka akan dikeluarkan dari tembok. Menjalankan tugas sebagai seorang ‘lelaki’.
Belum usai meredakan keterkejutanku, sebuah suara membuatku terlonjak. Suara dentuman besar yang membuat gempa kecil. Aku dan Hani buru-buru keluar rumah. Langit biru yang biasa kami lihat berubah menjadi hitam. Aku yakin itu bukan tanda hujan.
“Ada apa?” tanyaku pada wanita yang berlari menjauh dari sumber asap itu. Dia nampak ketakutan dan kebingungan. Mulutnya bahkan tak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, aku titipkan dia pada Hani. Sedangkan aku memilih menyeret kakiku ke sana.
Orang-orang berlarian, di ujung sana, aku melihat sosok lelaki. Alisku menyatu, masih belum memahami situasi yang terjadi.
“Nafa, lari! Para lelaki itu mencoba merobohkan tembok!” titah ibuku menarik pergelangan tangan.
“Kenapa mereka tiba-tiba melakukannya? Sebenarnya, apa yang terjadi, Bu?!”
“Mereka memberontak! Melakukan perlawanan karena merasa diperbudak atau apalah itu. Dasar! Memangnya kenapa mereka diperlakukan seperti itu coba? Itu ‘kan salahnya sendiri. Memang dasar makhluk buas! Cuma bisa melakukan kekerasan,” decak Ibu mengelus dadanya.
Aku terdiam. Entah aku yang aneh atau mereka yang berbeda. Ingin sekali kukatakan sesuatu, tapi aku urungkan. Yang ada justru aku yang akan dicaci maki. Tanpa berkata lagi, aku melepaskan cekalan Ibu dan berlari kencang menuju arah tembok. Menulikan telinga dari suara panggilan dari sosok wanita yang melahirkanku.
Aku mengatur napasku ketika sampai. Namun, udara yang penuh debu itu menyulitkan paru-paru. Kulihat para lelaki yang sibuk memasang sesuatu di tembok. Beberapa ada yang menghancurkannya dengan besi besar. Aku tak tahu apa namanya, tapi benda itu sukses membuat lubang kecil di tembok berumur nyaris seratus tahun.
“Apa yang kalian lakukan, Bodoh!”
Berhasil. Aku tahu jika berteriak saja mereka pasti mengabaikanku, makanya aku sengaja memperolok mereka. Kudengar mereka mudah tersinggung. Kini, seluruh perhatian aku dapatkan.
“Mengambil kembali hak-hak kami. Akan kami hancurkan tembok ini dan membuat kalian para perempuan sadar, jika kalian ini adalah penindas! Kami tak salah apa-apa. Kami juga korban! Yang salah itu leluhur kami!” Seorang lelaki tua maju dan menyampaikan keluh kesahnya. Tatapan matanya memerah, urat kemarahannya juga tercetak jelas di wajahnya.
“Lalu, bukannya apa yang kalian lakukan sekarang sama dengan leluhur kalian dulu? Membuat onar, teror, bahkan melakukan kekerasan?” tanyaku balik.
Mereka tidak membalas, sedang para perempuan nampak memiliki kekuatan. Mereka tersenyum miring di belakangku. Merasa berkuasa.
“Tapi, aku mendukung kalian dalam menghancurkan tembok itu.”
Semua orang menoleh ke arahku dengan wajah terkejut. Aku melanjutkan, “Bukan hanya kalian para lelaki yang menderita. Kami juga! Kami para perempuan merasa tidak berguna. Tidak bisa melakukan apapun kecuali tidur dan makan! Kalau begini, apa bedanya dengan para perempuan di zaman dulu? Kami seakan hanya sebagai penghasil keturunan. Apakah kalian tidak berpikir seperti itu?” tanyaku pada para perempuan yang masih berdiri di sana. Mereka saling bertukar pandangan. Tidak mampu membalas perkataanku.
Aku menikmati sejenak keheningan ini. Sebelum menarik napas, menyampaikan satu hal lagi. “Oleh karena itu, kita hancurkan saja tembok sialan ini! Dengan begitu, kita bisa hidup berdampingan. Membagi tugas serta peran tanpa ada diskriminasi lagi. Aku tidak menjamin akan adanya kebahagiaan di masa yang akan datang, tapi aku sudah muak! Aku ingin belajar dan pintar! Aku masih tidak terima kalah dengan Raka!” gerutuku tanpa sadar.
Aku menutup mulutku secepat kilat. Namun, terlambat, mereka tertawa mendengarnya. Termasuk adikku, Raka. “Nanti aku pinjamkan bukuku lagi, Kak. Kalau perlu, akan kuajari semua yang kuketahui,” usulnya.
“Aku juga akan mengajarimu memasak. Kau pasti tak bisa melakukannya, bukan?”
Satu per satu, lelaki menawariku untuk berguru pada mereka. Perempuan yang lain juga merengek dengan hal yang sama. Pada akhirnya, kemarahan kami mereda. Kami pun sepakat untuk menghancurkan tembok.
Kami perempuan memang tidak suka dikekang, ditindas, apalagi diperlakukan sembarangan. Namun, kami juga berhak mendapatkan apa yang kami inginkan. Bukankah semua manusia itu setara?
Penulis : Nafa
Editor : Ahmad Thohari