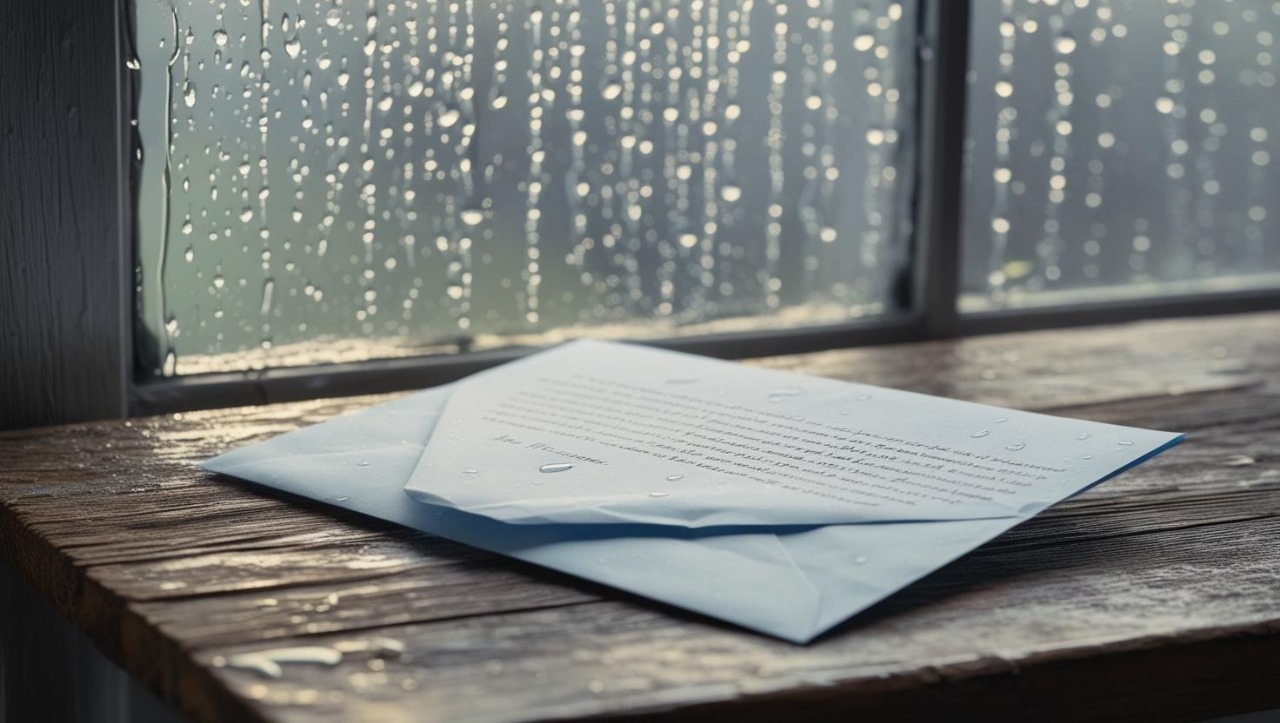Sumber gambar: Unsplash
“Kiw, kiw, Cewek! Gunungnya ukuran berapa, tuh?”
Tanganku refleks menyilang. Memberikan pertahanan tubuh seperti seorang prajurit yang hendak berperang. Namun, jika prajurit melakukannya dengan gagah berani, tubuhku justru bergetar ketakutan. Secepat mungkin kakiku melangkah, menjauhi makhluk paling mengerikan di muka bumi.
Bukan setan apalagi dajjal, melainkan laki-laki.
Saat aku masih kecil, laki-laki dan perempuan nampak sama. Perbedaannya mungkin hanya di gaya rambut dan berpakaian. Semakin hari, aku mengerti jika keduanya sungguh berbeda. Apalagi ketika masa-masa pubertas mulai menghampiri. Ketika bentuk tubuh yang mulai tumbuh sana-sini, saat itulah para lelaki mulai menatapku seperti mangsa.
Yang mereka lihat pertama kali adalah dadaku. Tumpukan lemak yang sudah kututupi sedemikian rupa, tetap saja tembus di pandangan mereka. Mulai saat itu juga, aku mulai membenci tubuhku sendiri.
“Dia tuh, enak banget gunungnya gede.”
Tapi, aku tak merasa seberuntung itu.
“Pasti lo populer di antara cowok-cowok, kan?”
Mereka bahkan tak melihat ke wajahku.
“Kok bisa segede itu, sih? Lo operasi, ya?”
Untuk apa? Membiarkan tubuhku menjadi objek fantasi mereka?
Dialog-dialog itu sering kali kudengar hingga aku sendiri muak untuk menjawab. Jawabanku yang selalu bertolak belakang dengan apa yang mereka asumsikan membuat mereka semakin mentertawakan. Mengataiku munafik, sok merendah, sok suci, atau yang lainnya.
“Naf, bisa bantu gak?”
“Kalau soal duit, gue gak bisa ngutangin,” ceplos perempuan yang duduk di sebelahku tanpa menoleh. Dia fokus dengan ponselnya.
Berbeda denganku, perempuan berjilbab itu cenderung bodoamat dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Meski keselamatan dunia dipertaruhkan, aku yakin seratus persen dia memilih untuk mengurung diri di kamar dan sibuk dengan sosial media.
Ini juga yang membuatku nyaman berteman dengannya. Dia tidak pernah bertanya tentang bentuk tubuhku meski hanya sekedar bercanda. Nafa lebih tertarik dengan kelanjutan film yang ditontonnya semalaman.
Kami pun dekat karena sama-sama penyendiri dan dijauhi oleh orang-orang. Terlalu aneh, terlalu abnormal.
“Pinjemin pisau,” pintaku melirik benda tajam yang berada di bawah kakinya. Diletakkan setelah dia mengupas mangga yang dinikmati sendiri tanpa menawarkannya padaku.
“Mangganya abis. Lo beli lagi sana,” ucapnya lagi.
Aku menarik napas. Minus berteman dengan Nafa adalah harus memiliki kesabaran tingkat dewa. “Gue bukan pengen motong mangga. Tapi, ini.”
Pandangannya akhirnya lepas dari ponsel. Perempuan itu mengikuti arah telunjukku. Ajaibnya, tangannya langsung meletakkan ponsel lalu menendang pisau sejauh yang dia bisa. Tatapannya biasanya memang datar, tapi ini sedikit berbeda.
“Lo mau cerita?” Dia bertanya sembari meraih tangannku yang awalnya menunjuk ke arah dada. Digengamnya erat, seolah takut aku akan berbuat yang aneh-aneh.
Pertanyaan sederhana itu membuatku ingin membuka mulut. Menceritakan segala hal yang sudah lama bersemayam dalam benakku. Sebuah cerita panjang yang belum pernah kuungkap. Aku tak mengharapkan solusi, tapi mulut ini tidak bisa berhenti.
Bahkan, tanpa kusadari, air mataku mulai keluar.
“Gue bukannya nggak bersyukur dengan kondisi tubuh ini. Cuma, kalau bikin gue sendiri nggak nyaman, terus buat apa? Gue bahkan udah nyoba menutupinya dengan pakaian yang longgar dan panjang. Tapi, nyatanya mereka tetap saja bisa melihat. Seolah-olah mata mereka memiliki kemampuan tembus pandang.”
Aku kembali memukul dadaku sendiri, pusat dari segala masalah dan kemarahanku.
“Gue … gue nggak ngerti. Kenapa gue dicap jalang hanya karena tubuh yang gue sendiri nggak pengen? Semakin gue membela diri, semakin mereka memaknai dengan presepsi mereka sendiri. Kenapa?!” raungku pada akhirnya, menghempaskan genggaman tangan Nafa dan memukul piring bekas mangga hingga pecah.
Nafa menyingkirkan pecahan piring itu tanpa protes. Padahal itu piring miliknya dan gadis itu tak suka barangnya seenaknya disentuh. Apalagi ini kupecahkan. “Manusia itu mempercayai apa yang ingin mereka percayai, bukan apa yang didengar atau dilihat. Jadi, meski lo ngebacot sana-sini, kalau mereka gak mau percaya, ya gak guna.”
Aku terdiam sejenak. Mencerna komentar Nafa sambil menghapus ingus. Tatapanku masih padanya yang keluar kamar untuk membuang pecahan piring. Di luar dugaan, dia mendengarkanku dengan baik. Penafsiranku tentang tatapannya memang benar, Nafa menjadi sosok yang peduli dan khawatir.
“Jadi, lo percaya gue?” tanyaku ketika dia kembali.
“Gak. Gue percayanya sama Tuhan,” ketusnya. Sok-sokan gengsi ternyata. Saat aku mengucapkan terima kasih pun, Nafa menghindari pandangan. Tangannya meraih lagi pisau yang dibuangnya. Mengarahkan mata pisaunya padaku sambil bertanya, “Masih butuh?”
Sejenak aku terdiam. Remaja perempuan itu memang sulit ditebak. “Nggak, deh. Gue pengen pinjem gunting daripada pisau,” kataku santai.
Nafa bingung, tapi dia tetap menurut. Memberiku gunting dan menyodorkan cermin sesuai perintahku. Aku lantas meraih benda di sekitar leherku. Tanpa keraguan, aku menggunakan gunting itu dengan handal. Nafa tak bertanya lanjut, tapi bola matanya melebar. Sejenak, dia tertawa.
“Siapa, sih? Yang menciptakan tradisi potong rambut sebagai tanda awal yang baru? Konyol banget,” komentarnya setelah aku memotong rambutku yang awalnya sepinggang menjadi hanya sebahu saja.
Aku ikut tertawa lepas. Dulunya aku menggunakan rambut panjangku untuk membantu menutupi dada. Padahal aku sendiri tak menyukai rambut yang panjang karena perawatannya yang menyusahkan. Kini, aku akan melakukan hal yang sukai dan membuatku nyaman.
Karena aku sudah menyadari jika apapun yang kukenakan, apapun yang aku lakukan, komentar akan selalu terlontar. Entah komentar yang baik ataupun yang buruk. Seperti mereka yang bebas berkomentar, aku juga bebas menanggapinya. Apalagi, kini aku punya jurus andalan ketika digoda oleh lelaki hidung belang.
“Anjay, gede banget. Ukuran gunungnya berapa, Mbak?”
Aku yang sekarang sedang memakai terusan tanpa lengan bewarna biru menoleh ke arah kumpulan remaja lelaki yang saling bersiul menatap tubuhku. Pelecehan ringan yang sama sekali tak mereka sadari. Aku berkoar-koar tentang hukum pelecehan pun pasti ditanggapi candaan olehnya.
Menunggu tawa para bajingan itu berhenti, aku turut tersenyum. Mengeja kata-kata yang Nafa ajarkan baru-baru ini.
“Memangnya burungmu ukuran berapa, Mas? Pasti kecil, ya?”
Persis yang mereka lakukan, aku terang-terangan menatap pusat tubuh para bajingan yang berdiri kaku. Lucunya, mereka lantas bergerak tak nyaman dan beberapa menutupi hal yang sudah tertutup sebelumnya.
“Hahaha! Gila lo, Syif!”
Mendengar tawa lantang Nafa, para bajingan tadi langsung pergi meninggalkan kami. Aku tersenyum lega sambil menunggu Nafa menyelesaikan tawanya.
“Gue gila ya gara-gara lo, Fa.”
“Tapi, mending jadi gila daripada stres, kan?” Nafa memegangi pundakku untuk menopang tubuhnya yang lemas karena kebanyakan tertawa. “Gimana? Udah puas? Berani melawan nggak semenakutkan itu, kan?”
Aku reflek merangkul pundak yang lebih mungil dibandingkan pundakku. Ternyata aku hanya butuh satu teman yang sepertinya. Selagi Nafa tak meninggalkan dan memberiku komentar yang buruk, itu sudah cukup.
Aku tak perlu membahagiakan semua orang. Aku tak perlu mendengarkan semua perkataan yang terlontar. Aku hanya perlu melakukan apa yang ingin kulakukan selagi itu tidak menyakitiku dan orang-orang yang berharga di sekitarku.
Cukup itu saja.
“Puas banget, Fa! Ada cara lain, nggak?”
“Gampang. Ini kan aslinya lemak, lo olahraga aja! Atau potong aja coba.”
“Lo cuma iri karena punyamu datar, kan, Fa?”
“Sialan! Ngelunjak lo, ya?!”
Kami pun saling kejar-mengejar dan melakukan perkelahian ringan. Mengabaikan pandangan orang-orang dan hanya fokus pada diri kami sendiri. Perlahan tapi pasti, aku mulai menerima apapun yang aku miliki.
Tamat.
Penulis: Nafa Azizah
Editor: Abril